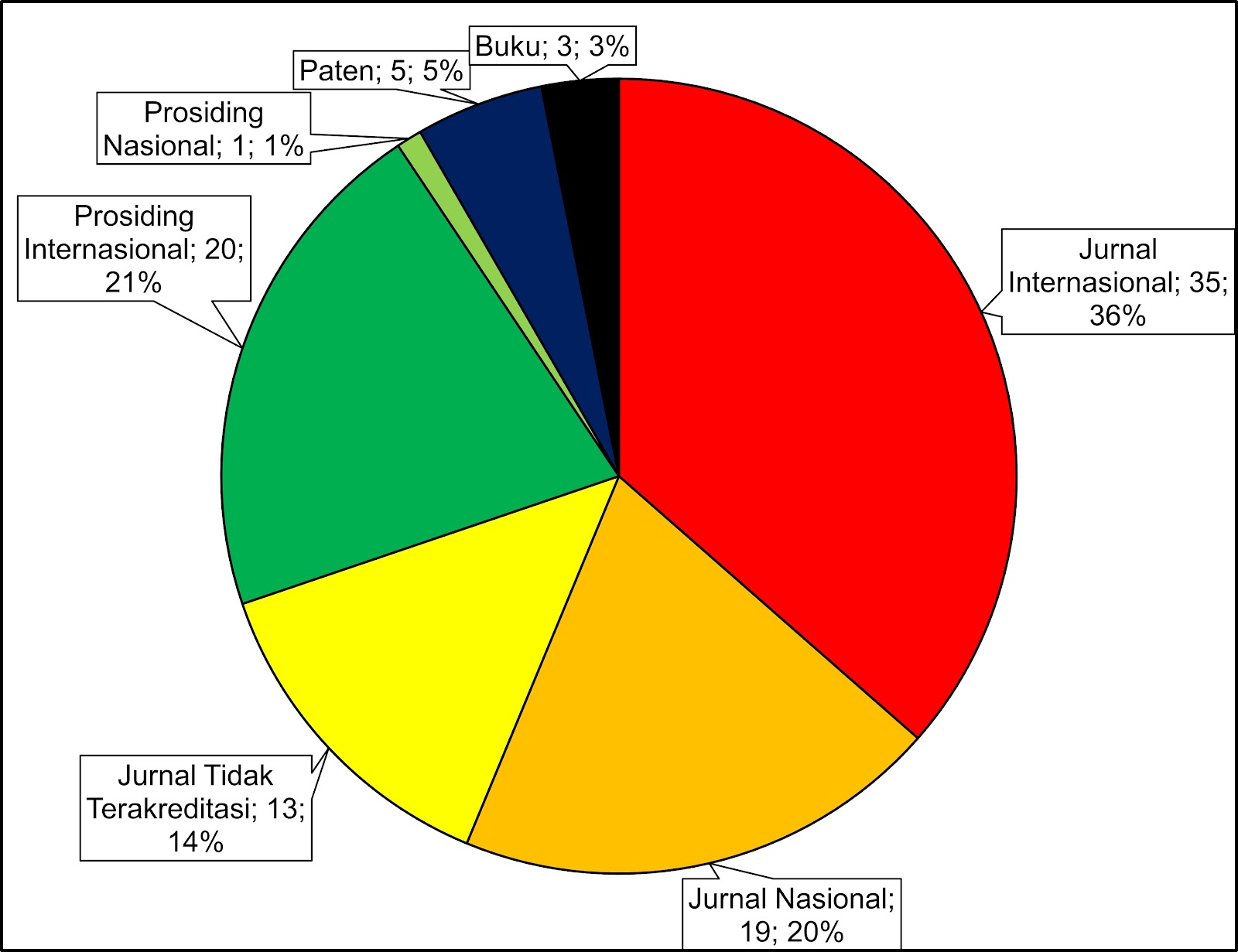Belum lama ini, saya membaca berita di website salah satu universitas domestik soal mahasiswa pascasarjana yang menyelesaikan kuliah S2-S3 dalam tiga tahun (!!!) dan menerbitkan 25 publikasi ilmiah dalam tiga tahun kuliahnya tersebut. Artinya, ada delapan publikasi ilmiah di jurnal internasional dalam setahun.
Lalu, seorang rekan kemudian membagikan berita soal dokter alumni S3 Belanda yang mendapatkan penghargaan dari MURI terkait rekor publikasi terbanyak selama studi doktoral, yakni 68 publikasi ilmiah! Saya memulai riset sejak 2018, yang artinya sudah 7 tahun terlibat di dunia litbang, dan publikasi di jurnal internasional masih tidak sampai 20.
Tidak ketinggalan pula, pemenang reality show kapitalis bertopeng pendidikan ajang kompetisi intelejensia mahasiswa Musim Pertama, yang saat ini masih mahasiswa S1 di universitas lokal, sudah publikasi belasan publikasi ilmiah, dua di antaranya sebagai penulis pertama. Mayoritas di jurnal internasional terindeks Scopus pula.
Walau demikian, setelah saya cek lagi di akun Scopus dan Google Scholar masing-masing individu tersebut, mayoritas adalah... systematic literature review (SLR) dan meta-analysis. Review article, bukan original research article. Ada, memang, original research article (kecuali pemenang reality show kompetisi pendidikan), tapi tidak sebanyak itu. Mayoritas, kalau bukan semuanya, dipublikasikan ketika sedang menempuh jenjang perkuliahan, sedikit sekali di luar perkuliahan.
Dari situ, saya jadi sering terpikirkan soal hakikat publikasi ilmiah. Sebenarnya apa, sih, yang dituju dari publikasi ilmiah ini? Publikasi ilmiah itu sebenarnya untuk apa? Kenapa sekarang normanya jadi seolah-olah lulus secepat-cepatnya dan publikasi sebanyak-banyaknya? In a sense, tren ini juga saya curigai mulai muncul di lembaga riset yang harusnya menelurkan publikasi berupa original research article, bukannya banyak-banyakan publikasi SLR dan meta-analysis.
Perlu diakui bahwa publikasi ilmiah negeri ini masih sedikit. Untuk ukuran negara sebesar Indonesia, data Scimago menunjukkan bahwa jumlah dokumen terpublikasi yang terindeks lembaga pengindeks komersial sejenis Scopus dan Web of Science baru berada di peringkat 37. Setingkat di bawah Singapura dengan jumlah penduduk yang... agak memalukan untuk membandingkan keduanya. Bahkan lebih rendah daripada entitas ilegal fasis rasis maniak genosida yang berada di peringkat 26. Ini belum bicara sitasi per dokumen dan H-Index yang paling rendah di antara 50 negara dengan dokumen terpublikasi paling banyak!
Kinda embarrassing, really...
Publikasi ilmiah memang salah satu indikator yang menunjukkan kualitas dan kemajuan riset sebuah negara. Masalahnya? Jumlah itu adalah indikator kualitas riset, bukan target riset! Publikasi ilmiah, seharusnya, bukan ajang gengsi-gengsian. Bukan ajang kompetisi kejar-kejaran banyak-banyakan, bukan! Jumlah publikasi ilmiah itu tidak lebih dari indikator, seberapa maju kualitas riset sebuah negara, bukan target yang harus dikejar!
Sepertinya ini yang disalahartikan oleh para pemangku kebijakan. Sadar bahwa publikasi ilmiah terindeks Scopus dan Web of Science masih sedikit relatif terhadap negara lain, akhirnya kuantitas digenjot habis-habisan. Tapi apakah tuntutan kenaikan kuantitas publikasi ini diimbangi dengan penambahan kuantitas anggaran? Apakah diimbangi dengan perbaikan fasilitas riset dan kenaikan gaji akademisi serta peneliti? Ya tentu saja... tidak. Justru makin ke sini makin diperketat, birokrasi dipersulit, bahkan anggaran riset turun dari Rp 26 triliun menjadi Rp 6-7 triliun. Tapi kuantitas publikasi harus diperbanyak.
Ini, logika dari mana?
Dari sini saya kira fenomena banyak-banyakan publikasi berbentuk SLR, meta-analysis, ditambah bibliometrik, mulai mencuat. Dengan krisis anggaran riset, penghematan anggaran demi proyek populis yang visi dan eksekusinya buruk, serta negara mengurangi pendanaan terhadap universitas yang makin kesini disuruh makin mandiri, sementara beban luaran makin banyak, para akademisi akhirnya mencari exit liquidity berupa menggunakan data sekunder, yang menghasilkan tiga jenis publikasi tersebut. Data sekunder, karena datanya sudah ada, dikerjakan oleh negara-negara lain yang ekosistem risetnya agak "mendingan" (karena tidak semuanya sehat juga), lalu tinggal ditelaah semua datanya dan diberi penafsiran dan kesimpulan sendiri dari kumpulan data itu. Kadang cuma membaca data saja, tidak ada analisis sendiri. Herannya masih terbit. Di jurnal terindeks Scopus pula.
Kalau sekadar exit liquidity, mungkin masih agak bisa diterima. Karena kepepet. Sementara pemberi anggaran sudah bawel menuntut luaran seperti kelelawar buah ketika melihat pepaya matang. Masalahnya, para akademisi dan peneliti tampaknya jadi ketagihan untuk terus menerus publikasi SLR, meta-analysis, dan bibliometrik. Pelatihannya muncul di mana-mana, untuk menggunakan tools bibliometrik dan SLR. Mahasiswa pascasarjana, yang harusnya disibukkan dengan original research, malah diajak banyak pihak untuk ikut nulis makalah SLR, meta-analysis, dan bibliometrik.
Mau dilihat dari manapun, fenomena ini jelas problematik. Publikasi ilmiah yang harusnya sebatas jadi indikator hasil riset, malah jadi ajang gengsi-gengsian dengan banyak-banyakan publikasi. Mana publikasinya dari hasil telaah data sekunder pula. Lalu ketika berhasil publikasi belasan hingga puluhan publikasi dalam setahun atau sepanjang masa studi, dianggap sebuah prestasi yang luar biasa.
Like, seriously?
Di mayoritas bidang, SLR dan bibliometrik itu seringkali hanya terpakai untuk bagian Latar Belakang/Introduction di manuskrip ilmiah. Meta-analysis paling berguna untuk riset bidang kesehatan, tapi bukan untuk dipublikasi sebanyak-banyaknya, melainkan ada kepentingan teknis untuk memandu original research. Mau dilihat dari manapun, tiga model publikasi itu tidak bisa dianggap sebagai primary research. Bukan riset utama, melainkan supporting research/riset pendukung. A mean, not a target.
Banyak-banyakan publikasi SLR, meta-analysis, dan bibliometrik, lalu berbangga dengan jumlah makalah yang terpublikasi itu, merasa telah berkontribusi dalam mendongkrak jumlah publikasi ilmiah negara, pada hakikatnya adalah sebuah bentuk kelucuan. Membanjiri dunia publikasi ilmiah, yang saat ini sudah tersaturasi, dengan jenis-jenis publikasi semacam itu, tidak lebih dari menghasilkan lebih banyak derau/noise dalam dunia riset, yang mulai jenuh dengan banyaknya publikasi dengan nilai tambah rendah, replikabilitas bermasalah, mitra bestari/reviewer yang lelah, dan entitas jurnal komersial yang terus menjajah.
Saat ini, dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus bukan lagi bukti bahwa kualitas publikasinya luar biasa bagus. Oversaturasi publikasi dan mental kapitalistik penerbit jurnal komersial akhirnya menjadikan standar publikasi seringkali melonggar, dan ini sudah menjadi concern di dunia ilmiah internasional.
Akhirnya, akademisi semodel begini hanya berbangga-bangga dengan jumlah publikasi saja. Bukan kualitas publikasi, bukan peran publikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi karena jumlahnya banyak dan terindeks Scopus. Lalu ketika pola seperti ini dikritik, malah menganggap si pengkritik itu iri, dengki, hasad, tidak suka dengan prestasi orang lain, you name it.
Padahal masalahnya yang dikritik adalah fenomena banyak-banyakan publikasi yang cuma jadi derau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di tengah dunia publikasi ilmiah yang terlalu banyak masalah. Tidak ada kaitannya dengan iri, hasad, dan sebangsanya. Hanya akademisi dan manusia berotak picik dan sempit yang berpikir seperti itu.
Publikasi semodel SLR, meta-analysis, dan bibliometrik ada pangsanya sendiri, tapi yang jelas bukan sebagai arah publikasi utama. Publikasi tersebut eksis sebagai pendukung dari tujuan utama: memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut bergantung pada original research, yang menghasilkan publikasi berupa original research article.
Tidak ada ilmuwan/akademisi yang membangun karir dari publikasi SLR, meta-analysis, dan bibliometrik. Kalau ada, itu ilmuwan kualitas rendah yang tidak punya kontribusi apa-apa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mungkin tidak berguna dan tidak paham sama sekali ketika harus melakukan original research, karena bisanya cuma pakai data sekunder.
Tampaknya, Goodhart's Law dapat diberlakukan untuk fenomena ini.
"
When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure."
Jumlah publikasi itu fungsinya hanya sebagai ukuran, bukan target. Ketika jumlah dijadikan sebagai target, sebagai ajang gengsi, sebagai ajang hebat-hebatan, maka jumlah publikasi bukan lagi jadi alat ukur yang bagus.
Budaya bangga-banggaan dengan jumlah ini selayaknya dikurang-kurangi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah hampir mengalami kekalahan di Perang Hunain. Apa mentalitas kaum muslimin pada saat Perang Hunain? Berbangga dengan jumlah. Merasa tidak terkalahkan. Sampai Allah SWT menegur umat Islam dengan cara demikian, supaya tidak usah sombong dengan jumlah yang banyak.
Bagi akademisi/Peneliti sungguhan, kualitas >>> kuantitas. Tidak apa-apa hanya bisa publikasi 1-2 makalah tiap tahun. Bahkan mungkin baru bisa publikasi sekali dalam dua tahun. Utamakan kualitas, bukan kuantitas. Utamakan kebermanfaatan riset untuk dunia ilmiah, ilmu pengetahuan, atau aplikasi dunia nyata (tergantung jenis risetnya), tidak usah ngoyo dengan banyak-banyakan jumlah. Karena riset berkualitas bagus dan kuantitas banyak dalam waktu singkat itu sama utopisnya dengan berharap merkuri bisa berubah menjadi emas hanya dengan memaparinya dengan netron dari sumber AmBe, tidak ada dalam realita.
Bagi yang masih berbangga-bangga dengan jumlah publikasi, tapi hanya berbekal data sekunder dan hanya menjadi derau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semoga mau sadar dan mulai lebih fokus pada kualitas riset di original research.