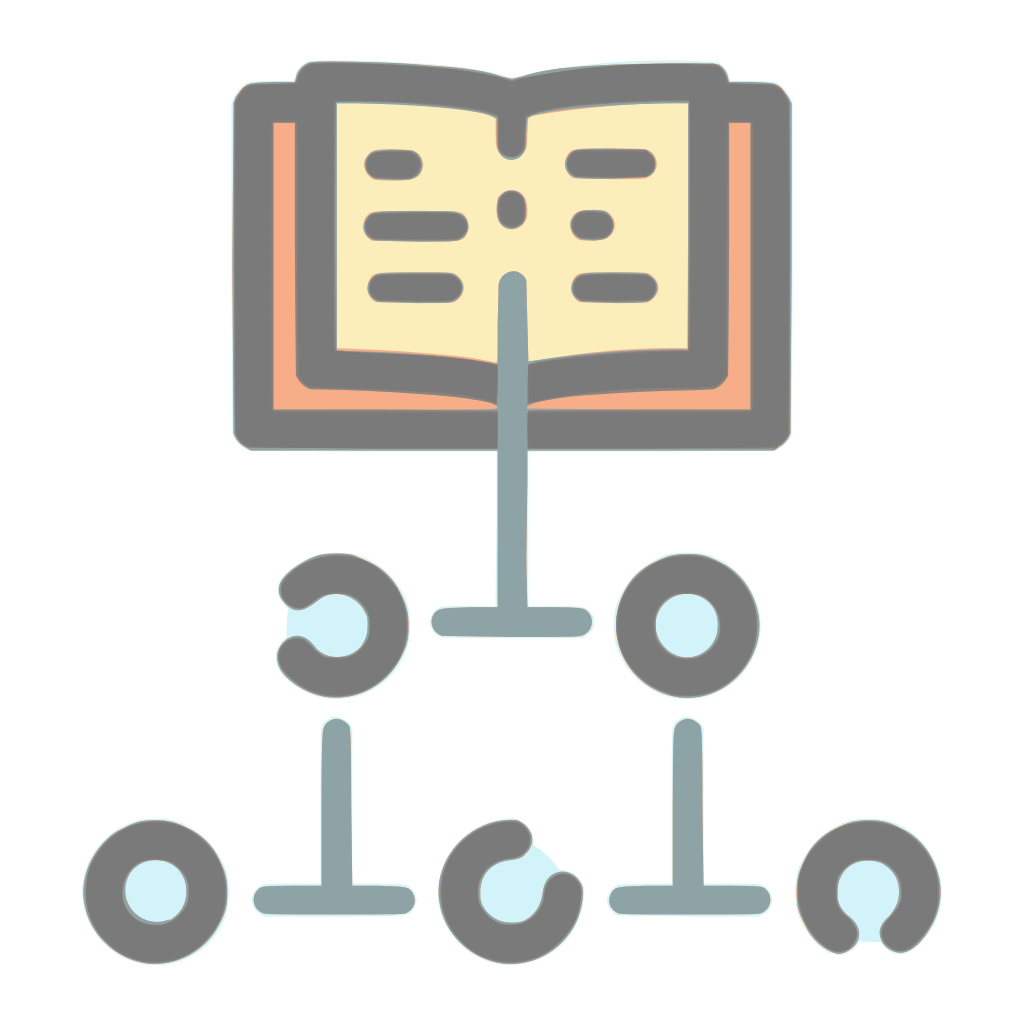Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah seorang manusia fana yang semasa hidupnya mencurangi para dewa, khususnya Zeus. Sisyphus pernah memperdaya Thanatos dan mengikatnya sehingga dia bisa kembali dari kematian. Tapi karena Thanatos tidak bisa melakukan tugasnya, manusia tidak bisa mati, dan Ares menjadi jengah karenanya. Akhirnya, Ares mengintervensi dan membebaskan Thanatos dari rantai pengikatnya, lalu melemparkan Sisyphus pada Thanatos untuk dikirim ke Dunia Bawah yang dikuasai Hades.
Akibat keangkuhan Sisyphus yang merasa lebih hebat dari para dewa, Hades menghukumnya dengan menyuruh Sisyphus untuk mendorong batu besar ke puncak bukit. Namun, setiap kali Sisyphus hampir mencapai puncak bukti, batu itu menggelinding kembali ke dasar bukit, dan Sisyphus harus mendorongnya kembali ke atas. Proses ini terulang selamanya. Tidak peduli seberapa kerasnya Sisyphus berusaha, dia dikutuk tidak pernah bisa mencapai tujuannya.
Dalam literatur, mitologi Sisyphus ini digunakan sebagai alegori untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang sulit dilakukan tapi tidak akan pernah berhasil. Dalam istilahnya Pampam dari opera sabun Tuyul dan Mbak Yul, "Gagal maning, gagal maning, Son!" Ironisnya, upaya Samson dan Pampam untuk menangkap Ucil dalam serial tersebut adalah representasi pas dari Sisyphean Effort. Capek-capek berusaha, gagal maning-gagal maning. Sudah berhasil meringkus Ucil, lepas lagi dari markas mereka.
Sisyphean Effort ini pada dasarnya banyak terjadi di dunia nyata, dan seringkali pelatuknya adalah arogansi seseorang. Dalam teknologi reaktor nuklir, misalkan, obsesi terhadap reaktor fusi nuklir bisa dianggap sebagai Sisyphean. Sudah riset lebih dari 50 tahun, tidak pernah juga berhasil untuk membangun sistem yang komersial apalagi terjangkau. Uang sudah keluar sangat besar, tapi mundur lagi mundur lagi estimasi waktu komersialisasinya. Sementara keekonomiannya masih tanda tanya besar. Kalau tidak ekonomis, tidak ada yang mau beli kecuali dengan subsidi superbesar, padahal ada opsi lain yang secara ekonomis jauh lebih logis (reaktor fisi nuklir).
Di sektor energi secara umum, upaya dekarbonisasi dengan 100% energi terbarukan juga merupakan Sisyphean Effort. Energi terbarukan dengan segala limitasi fisisnya tidak memungkinkan dekarbonisasi total, kecuali dengan mengorbankan reliabilitas sistem ketenagalistrikan, harga energi supermahal, availabilitas energi rendah, itupun kemungkinan besar masih harus bergantung pada energi fosil ATAU menyerah pada degrowth, yakni konsumsi energi dikurangi. Itupun belum tentu berhasil pada rentang waktu yang diharapkan. Usaha superbesar, hasil seadanya.
Di sektor politik, "memperbaiki demokrasi" secara teknis termasuk Sisyphean. Karena memperbaiki itu asumsinya bahwa sebuah sistem itu sejak awal bisa bekerja. Demokrasi tidak. Demokrasi tidak pernah bekerja sebagaimana mestinya sejak akarnya, karena klaim "perwakilan" itu utopis sebagaimana menyerahkan kedaulatan di tangan masyarakat itu utopis. Karenanya, klaim suara mayoritas pun utopis. Kedaulatan tidak pernah pernah berada di tangan rakyat, melainkan di tangan oligarki. "Suara mayoritas" hanya sebatas mayoritas dalam memilih antek oligarki dan tiran mana yang lebih disukai masyarakat.
Jadi, apa yang mau diperbaiki dari demokrasi? Tidak ada. Karena konsep dasarnya sendiri sudah rusak darisananya. Hanya arogansi manusia yang merasa vox populi vox dei adalah sebuah keniscayaan mutlak yang membuat Sisyphean ini terus diyakini bisa terwujud, meski keyakinan itu terus menerus menggelinding ke bawah bukit ketika dikira hampir berhasil.
Segala usaha untuk "memperbaiki demokrasi" tidak lebih dari Sisyphean Effort. Manusia-manusia yang nalarnya masih bekerja dengan baik selayaknya tidak mempersulit hidupnya yang sudah dipersulit secara sistemik dengan melakukan sesuatu yang sia-sia.